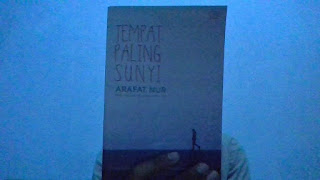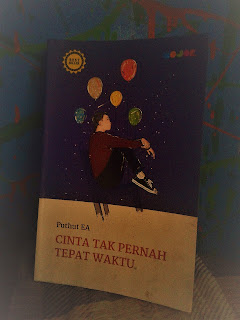Pilihan Ketiga yang Diambil Lelaki Tua

dokumentasi pribadi. Di beranda rumah panggung khas Bugis, selepas menerima panggilan telepon, seorang berkopiah hitam duduk. Sorot mata lelaki tua itu tajam. Seolah ada benda di atas sana yang ia pandangi lekat-lekat. Beberapi kali ia menghela nafas. Mencoba menenangkan diri. Bahkan riuh anak kecil di jalan depan rumahnya sama sekali tidak menarik perhatiannya. Lelaki tua itu pun beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah perlahan di atas lantai kayu yang berderit setiap kali kaki memijak. Bila orang lain yang berjalan di atas rumah lelaki tua itu, mungkin saja orang itu akan bergidik ketakutan. Was-was. Bagaimana tidak, lantai rumah itu sudah tidak kokoh lagi. Ruas-ruas bekas santapan rayap telah tampak di sana sini. Jika kaki terlalu kuat berpijak atau kalau sengaja ditekan kuat-kuat, maka akan terdengar bunyi kreks! Seperti suara kerupuk atau wafer saat pertama kali dikunyah. Rumah panggung miliknya memang sudah tua. Ia membangun rumah itu ketika usianya hampir mencap